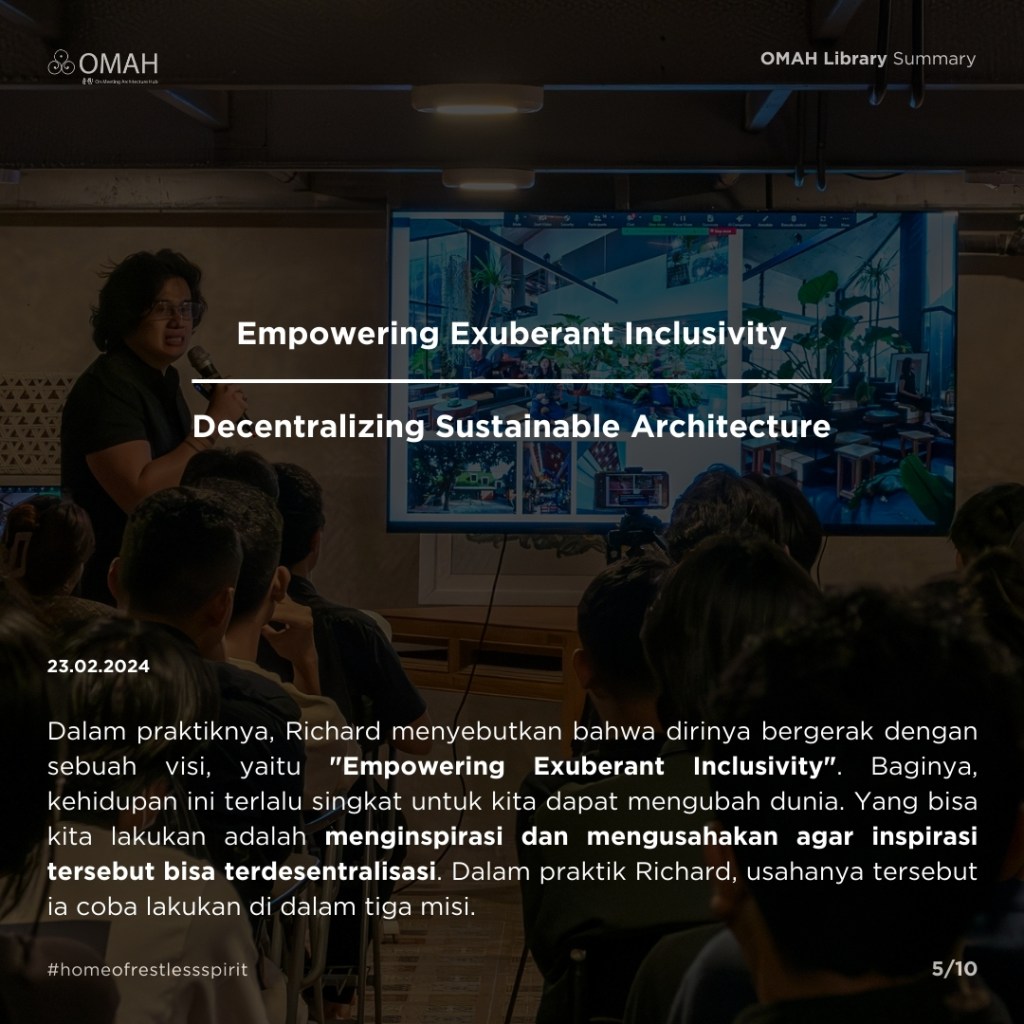Summary Kelas Arsitek(tur) Mumpuni Ep. Sutrisno Murtiyoso
Di hari Minggu yang telah lalu, Sutrisno Murtiyoso membuka sesi kelas dengan mengutarakan keheranannya bisa diundang untuk berbicara dalam kategori “Arsitek Mumpuni”. Baginya, dirinya bukanlah arsitek, apalagi mumpuni. Ia bahkan sudah sejak lama berhenti berpraktik. Ia kemudian mendefinisikan kata mumpuni sebagai pengembangan dari kata “mampu” dan “empu” yang dalam bahasa Jawa diartikan sebagai orang yang memiliki keahlian lebih. Menurutnya, empu arsitektur di Indonesia cukup banyak. Beberapa di antaranya mengantarkan Sutrisno Murtiyoso sampai di titik ini.
Sutrisno Murtiyoso melanjutkan bercerita tentang perjalanan berarsitekturnya. Ia mulai dari cerita di masa kecilnya saat masih tinggal di sebuah desa di gunung. Ia merasa beruntung karena tempatnya dilahirkan dan dibesarkan memberinya banyak penyadaran mengenai konstelasi ruang, bahkan sebelum dirinya mengenal arsitektur. Di masa itu, pintu rumah-rumah desa umumnya tidak pernah tertutup di siang hari. Sutrisno kecil pun bebas keluar-masuk untuk bermain sehingga ia bisa mengamati keberagaman konfigurasi ruang di rumah teman-temannya. Belum lagi ditambah dengan kepercayaan tentang adanya penunggu di beberapa lokasi yang membuat Sutrisno lebih memperhatikan lagi konstelasi ruang dalam skala yang lebih besar.
Ia baru mengetahui adanya disiplin arsitektur ketika dirinya melanjutkan SMA di Kota Semarang dan menyaksikan karya-karya mahasiswa dan dosen di suatu pameran yang diselenggarkan oleh program studi arsitektur Universitas Diponegoro. Saat melanjutkan kuliah di jurusan tersebut, awalnya ia merasa bahwa arsitektur adalah pekerjaan yang mudah. Tinggal mendesain, mencari orang yang bisa membangunkan, dan selesai.
Keadaan berbalik ketika ia dipertemukan dengan buku Intentions in Architecture karya Christian Norberg-Schulz, seorang empu dari luar negeri di pandangan Sutrisno. Ia tiba-tiba merasa tidak mengetahui apa-apa dan menjadi tidak yakin dengan arsitektur. Ia berhasil lulus hanya atas dorongan dua perempuan luar biasa dalam hidupnya, yaitu ibunya dan istrinya.
Ia lalu bertemu dengan satu empu lain dari Jepang, yaitu Koji Sato, sosok yang membuatnya malu sebagai warga negara Indonesia atas pengetahuannya tentang arsitektur Indonesia yang kalah jauh dari sang empu. Sejak saat itulah, ia merasakan pentingnya ada orang Indonesia yang mengkaji arsitektur Indonesia. Pertemuan Sutrisno Murtiyoso dengan tiga orang empu, yaitu Yuswadi Saliya, Sandi A. Siregar, dan Haryoto Koento, kemudian membawanya menjadi bagian dari pendirian Lembaga Sejarah Arsitektur Indonesia (LSAI).
Melalui LSAI, Sutrisno bertemu dan berkenalan dengan lebih banyak empu lainnya. Ia menyebutkan empu Ardi Pardiman yang biasa mengadakan “kuliah” di mana-mana bahkan hingga di warung pinggir jalan dan empu Josef Prijotomo yang selalu menjadi lawan tandingnya dalam diskusi.
LSAI juga memungkinkan Sutrisno yang masih merupakan lulusan baru pada saat itu terlibat dalam banyak hal. Melalui empu Gunawan Tjahjono yang memperkenalkannya dengan empu Koentjaraningrat, ia ditugasi mengkaji arsitektur Islam di Indonesia hingga terlibat dalam penulisan Indonesian Heritage Series yang digagas oleh Kementerian Pariwisata. Melalui empu Ahmad Noe’man, ia terlibat dalam tiga seri Festival Istiqlal hingga dirinya banyak berkeliling Indonesia dan bahkan terlibat dalam pendokumentasian Masjid Al-Akbar di Surabaya dan Masjid Agung Jawa Tengah di Semarang.
Pada tahun 2008, Sutrisno dihubungi oleh empu Ronald G. Knapp yang sedang menulis mengenai arsitektur Cina di Asia Tenggara dan memintanya untuk meneliti kampung halamannya sendiri, Parakan. Akibat keterlibatannya di dalam penelitian arsitektur Cina di Indonesia, ia terkoneksi dengan Chinese Heritage Society di Singapura dan bertemu dengan empu Leo Suryadinata yang menugasinya untuk mendokumentasikan dan meneliti kelenteng di Jawa dan Bali. Terakhir, pada tahun 2022, Sutrisno diundang untuk menyusun buku mengenai bangunan-bangunan lama Bank Indonesia, atau yang semula bernama The Javasche Bank, yang membuka kesempatan baginya untuk meneliti masa-masa awal masuknya arsitektur modern di Indonesia.
Setelah bercerita pengalaman, Sutrisno Murtiyoso melanjutkan dengan memaparkan pandangannya lebih jauh mengenai praktik arsitektur di Indonesia saat ini. Ia mengamati bagaimana kebanyakan ilmu yang dipakai di dalam pendidikan arsitektur kita berasal dari Eropa dan Amerika, yang mana hal tersebut tidaklah salah dan bagus untuk memperkaya pengetahuan. Akan tetapi, ia menegaskan mengenai perbedaan perspektif dan pentingnya Indonesia memiliki sudut pandang sendiri di dalam membangun arsitekturnya.
Menurut Sutrisno, lingkungan alam yang berangkat dari masyarakat petani, khususnya petani sawah, menjadi faktor penentu terbesar yang membentuk budaya cara orang Indonesia memandang, menyikapi, dan membentuk gagasan ruang yang dilahirkan di dalam arsitekturnya. Demikian pula pola-pola kemasyarakatannya yang tercermin pada cara orang-orang memperlakukan sesamanya. Di lingkungan petani, hampir tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Bahkan, terlihat ada pengistimewaan terhadap perempuan yang dianggap sebagai “pemilik rumah”, sebagaimana dalam adat Minangkabau. Hal tersebut sangat berbeda dengan kawasan lain dengan kondisi lingkungan yang lebih keras di mana kekuatan fisik diutamakan, sehingga posisi laki-laki dianggap lebih tinggi daripada perempuan.
Ketika masyarakat petani berkumpul membentuk kerajaan, stratifikasi yang jelas pun muncul. Hal tersebut turut memengaruhi cara kita mengolah ruang di dalam rumah dan mengklasifikasikan tamu, apakah ia dapat dibawa hingga ke ruang privat atau cukup di depan saja. Ketiga unsur inilah, yaitu lingkungan alam, tata laku kemasyarakatan, dan budaya, yang pada akhirnya mengarahkan perwujudan ruang yang kita sebut sebagai arsitektur.
Mengapa hal tersebut kemudian masih belum banyak dipahami? Menurut Sutrisno, arsitek memiliki dua buah sisi yang perlu dikuasai, yaitu keterampilan yang berkaitan dengan “bagaimana” menghasilkan sesuatu dan kesarjanaan yang berkaitan dengan tanggung jawab untuk menjawab pertanyaan “mengapa”. Mengapa arsitekturnya dibuat demikian? Masalahnya, arsitek muda masih kini masih lebih banyak yang berkonsentrasi pada sisi yang pertama dan kesulitan menjawab pertanyaan mengapa, pertanyaan yang seharusnya dijawab dengan pengetahuan humaniora dan kesejarahan.
Penyebabnya, menurut Sutrisno, adalah sistem pendidikan kita yang masih banyak menjalankan program sebagaimana ketika Technische Hooge School (THS), sekarang Institut Teknologi Bandung (ITB), didirikan. Padahal, tujuan pendidikan arsitektur saat itu memang hanyalah untuk menghasilkan tenaga bumiputera yang terampil untuk melaksanakan hasil pemikiran arsitek yang kebanyakan orang Belanda. Lebih dalam mengenai hal tersebut telah diulas oleh David Hutama di dalam buku dan penelitiannya yang juga sempat disampaikan di salah satu kelas OMAH Library.
Ada tiga hal yang menjadi perhatian Sutrisno di dalam pengamatannya terhadap aspek arsitektur Indonesia.
- Keragaman
Sutrisno menyoroti sudah banyaknya keragaman arsitektur Indonesia terekam, tetapi sejarah di balik terjadinya keragaman tersebut tidak banyak diketahui. Pada akhirnya, keragaman seringkali dilihat sebagai sesuatu yang berdiri sendiri. Akibatnya, ketika diminta untuk mendeskripsikan arsitektur Indonesia, kita seringkali hanya mengambil salah satu saja dari keragaman tersebut dan langsung menyebutnya sebagai arsitektur Indonesia. - Perkembangan
Seringkali kita menganggap apa yang kita sebut puncak arsitektur Indonesia sebagai sesuatu yang sudah ada sejak dahulu kala. Padahal, ia merupakan hasil perkembangan yang panjang sekali. Sutrisno mencontohkan joglo yang banyak dianggap sudah ada sejak masa Prabu Jayabaya. Padahal, menurut Sutrisno, kemunculannya justru dipengaruhi oleh masuknya Islam. Semula, dalam ibadah Hindu-Buddha, hanya pemimpin yang berada di bawah naungan. Sementara itu, dalam ibadah umat muslim, seluruh jama’ah berada di bawah satu atap bersama sang imam. Pada akhirnya, atas kebutuhan membangun bentang yang cukup lebar, pengetahuan konstruksi kayu dari yang sederhana pun berkembang. Baru kemudian, saat kekuasaan berpindah, konsentrasi keahlian membangun menjadi ditumpahkan ke keraton. - Pandangan
Aspek yang terakhir ini merupakan akibat dari dua aspek sebelumnya. Kurangnya pemahaman menyebabkan kita menjadi cenderung mudah berenjana dan meromantisasi sesuatu. Pada akhirnya, visi untuk memajukan arsitektur Indonesia menjadi sebatas mengaplikasikan apa yang bisa dilihat di Taman Mini.
Berdasarkan penelitian Sutrisno, nusantara sudah ditinggali manusia bahkan sejak abad 45 SM. Keberadaan manusia menandakan telah terjadinya pengolahan ruang, entah itu sudah dapat dikatakan sebagai arsitektur atau belum. Sutrisno mencoba menjelaskan secara sederhana. Pada masa berburu dan mengumpulkan makanan (austromelanesoid), secara arsitektural, denah hunian berbentuk lingkaran. Contohnya masih banyak dapat dilihat di kawasan timur Indonesia.
Ketika gelombang austro asiatik yang membawa budaya padi ladang masuk dari asia tenggara daratan, lahirlah denah persegi dan lantai panggung. Di Halmahera, kita masih bisa menemukan bangunan percampuran dari kedua budaya tadi yang membentuk denah segi-delapan. Karya-karya megalitik, seperti punden berundak, juga masuk di masa ini.
Gelombang berikutnya, yaitu austronesia yang masuk ke nusantara melalui jalur laut, kemudian membawa budaya sawah irigasi. Berbeda dari ladang dan sawah tadah hujan yang berpindah-pindah, teknologi irigasi memungkinkan terbentuknya kepemilikan lahan. Arsitektur pun terkonsentrasi pada keluarga batih atau inti. Ukuran rumah mengecil dengan tetap berkumpul. Terbentuklah kampung atau desa.
Setelah Masehi, barulah pengaruh-pengaruh kebudayaan dari belahan dunia lain masuk. Mulai dari Asia Selatan, Timur, dan Barat yang membawa pengaruh keagamaan Hindu, Buddha, dan Islam. Dilanjutkan dengan pengaruh kapitalisme Eropa yang membawa agama Kristen dan kolonialisme Belanda yang paling lama memengaruhi sistem kehidupan kita. Setelah merdeka, Amerika sebagai negara pemenang Perang Dunia II justru paling besar memengaruhi masuknya arsitektur modern di Indonesia. Abad 21 saat ini kemudian menjadi tanda tanya, ketika kita sudah menisbahkan diri sebagai warga dunia global tetapi belum bisa banyak berkomentar mengenai apa yang akan kita lakukan terkait status tersebut.
Sutrisno kemudian menyebutkan tiga hal mendasar yang perlu tetap diperhatikan di dalam menyikapi arsitektur Indonesia masa kini, sekalipun ia sendiri masih mempertanyakan poin yang terakhir.
- Memenuhi kebutuhan orang Indonesia
Kebutuhan orang Indonesia sudah pasti akan berbeda dengan kebutuhan masyarakat belahan dunia lainnya, sekalipun dalam konteks global masa kini. Oleh karenanya, memahami bagaimana masyarakat kita memandang ruang menjadi penting, tidak hanya di rumah tetapi juga di bangunan-bangunan lainnya. - Selaras dengan lingkungan Indonesia
Ketika membahas poin ini, Sutrisno mengomentari banyaknya bangunan di Indonesia yang dibangun dengan dinding kaca. Padahal, Indonesia dengan karakter iklim tropisnya mendapatkan sinar matahari yang melimpah ruah. Pada akhirnya, kita sibuk menutup kembali dinding-dinding kaca tadi dengan gorden untuk menghindari panas. Menurutnya, strategi pencahayaan alami tidak perlu dilakukan sampai membuat bukaan sebesar itu. - Memancarkan citra Indonesia
Poin ketiga menjadi poin yang banyak dibicarakan tetapi justru dipertanyakan oleh Sutrisno. Jika dua yang sebelumnya telah terpenuhi, apakah kita masih perlu berusaha memancarkan citra Indonesia? Jika iya, citra Indonesia seperti apakah yang dimaksud?
Sutrisno mengingatkan bahwa sebenarnya usaha membangun arsitektur Indonesia sudah dicanangkan sejak lebih dari satu abad yang lalu, ketika arsitek-arsitek Belanda pertama kali datang ke nusantara. Salah satunya ada Eduard Cuypers yang menyatakan bahwa arsitektur Hindia-Belanda membutuhkan pendekatan khusus, tidak bisa membawa saja arsitektur dari Belanda. Meskipun Cuypers belum dapat menggambarkan secara utuh, keinginan itu setidaknya sudah ada. Percobaan-percobaan pun dilakukan, mulai dari yang paling mudah, seperti menempelkan ragam hias kesukuan secara mentah-mentah pada bangunan.
Percobaan yang sedikit lebih mendalam kemudian dilakukan dengan melihat bahwa arsitektur nusantara memiliki tektonikanya sendiri. Dahulu, bahan-bahan organik dari alam banyak digunakan. Meskipun keadaan sekarang sudah sedikit berbeda, beberapa teknik tetap dapat dikembangkan.
Pendekatan terakhir yang paling jarang dilakukan adalah memahami cara masyarakat memandang dan menyikapi ruang. Namun, justru itulah yang menurut Sutrisno menjadi dasar mewujudkan arsitektur bagi semua orang. Contoh pendekatan ini ditemukan Sutrisno dalam karya-karya Thomas Karsten, seperti Teater Sobokartti di Semarang dan Permukiman Kwarasan. Karya tersebut dirasakan Sutrisno memunculkan suasana Jawa yang sangat kental, sekalipun dibangun dengan teknik yang modern.
Sutrisno kemudian menutup pemaparannya dengan menyebutkan permasalahan-permasalahan arsitektur Indonesia masa kini yang perlu disikapi: selera dan gaya hidup yang sudah mulai mendunia, persamaan dan pemerataan, perlindungan alam, lingkaran karbon, dan teknologi. Permasalahan terakhir menjadi yang cukup krusial menurut Sutrisno dalam konteks masa kini. Jika kita tidak bisa menyikapi semua permasalahan sebelumnya sebagai manusia, kelak kita akan dikendalikan oleh teknologi. Di akhir, Sutrisno memberikan pertanyaan yang menggelitik. Akankah kita lebih memilih mengembangkan potensi AI (Arsitek Indonesia) ataukah AI (Artificial Intelligence)?
Abimantra Pradhana: Selama 5 tahun terakhir, saya merasa cukup bangga melihat sudah mulai banyak dorongan untuk generasi muda saat ini kembali menggali diskursus arsitektur di Indonesia. Rasanya akan seru jika catatan-catatan temuan para senior ini juga dijadikan arsip, sekaligus diadakan diskursus agar ada integrasi antara generasi junior dan senior sehingga tongkat estafet dapat berpindah. Pertanyaan saya, adakah era yang masih hilang dalam sejarah arsitektur Indonesia yang masih perlu digali kembali sebagai tongkat estafet untuk diteruskan kepada kami?
Sutrisno Murtiyoso: Agak sulit melihat ada tidaknya kesenjangan karena adanya perbedaan tempo perkembangan di setiap masa. Dahulu, perubahan kecil bisa memakan waktu hingga ratusan tahun. Saat ini, waktu satu bulan saja sudah bisa mengubah banyak hal. Sebagai peminat sejarah, setiap era tentunya penting untuk digali. Karena masa yang sangat panjang itulah, penelitiannya membutuhkan banyak pihak. Inilah tujuan pendirian LSAI, yaitu mengumpulkan para peneliti yang berminat terhadap sejarah pada kurun waktu tertentu untuk kemudian disatukan. Akan berguna sekali jika hal tersebut bisa dilanjutkan.
Chalvin Tri Ananta: Bagaimana opini Bapak mengenai jiwa arsitektur di dalam mendesain? Apakah kita lebih perlu menyesuaikan arsitektur dengan lingkungan saat itu atau justru mengambil preferensi dari masa lalu?
Sutrisno Murtiyoso: Dalam dimensi waktu, kebutuhan kita terus berubah. Anda mungkin berasal dari generasi yang sudah memegang HP sejak lahir. Sementara itu, saya baru mengenal telepon rumah saat SMP. Apakah hal tersebut perlu dilanjutkan? Kan tidak. Menurut saya, sebagai seorang arsitek, yang lebih penting adalah mengenal tata cara sehari-hari yang berlaku di suatu masyarakat yang pastinya akan berbeda di setiap tempat, sehingga desain yang kita buat akan lebih sesuai dengan kebutuhan.
Eka Swadiansa: Saya ingin sedikit bercerita mengenai kesan pertama saya dengan LSAI. Saya melihat LSAI sebagai tempat berkumpulnya guru-guru hebat. Akan tetapi, ketika diskusi, mereka bisa duduk bersama dengan melepas almamater masing-masing. Itu yang saya hargai. Pada tahun 2010, di UKDW Jogjakarta, saya diajak bergabung dan disuruh mempersiapkan tulisan oleh dosen saya, hingga dihasilkanlah buku. Di situ, saya terkejut. Kami yang junior sudah dianggap pantas ikut berkontribusi, bersanding dengan para senior. Saya merasa kedua hal tersebut sudah sulit ditemukaan saat ini dan menjadi hal yang patut diteladani.
Altrerosje Asri: Saya teringat masa ketika saya baru lulus dan melihat banyaknya komunitas yang hobi berdebat. Mimpi Pak Josef Prijotomo akan adanya sebuah renaissance pemikiran mungkin terjadi pada masa kemunculan LSAI, AMI, dan lain-lain. Saat itu, “perang” antar-mazhab benar-benar terjadi. Tidak ada sungkan untuk bertentangan pemikiran antara junior dan senior. Saya kagum dengan isi otak dan kesanggupan mereka untuk terus berseberangan dan menjadikan diskusi sebagai keseharian, bahkan guyon. Melihat kondisi saat ini, saya bertanya-tanya. Mengapa kita belum bisa menjadi seperti dahulu?
Realrich Sjarief: Bersejawat, berjejaring, dan menemukan orang-orang yang sevisi tidaklah mudah. Dalam diskursus, pergerakan juga bukan hanya tentang wacana tetapi juga agen yang membawa perubahan. Berdasarkan pengalaman panjang Bapak, apa sebenarnya permasalahan mendasar di dalam kaderisasi?
Sutrisno Murtiyoso: Dahulu, keterbatasan komunikasi menjadikan orang-orang sangat berusaha memanfaatkan kesempatan. Dengan kemudahan komunikasi saat ini, keeratan justru berkurang. Kita mungkin sering hanya menyempatkan waktu 5 menit berbicara dengan seseorang dan berpikir untuk melanjutkannya pekan atau bulan depan karena ada urusan lain yang perlu diselesaikan. Tanggung jawab pun semakin banyak dengan semakin rumitnya birokrasi. Saat ini, dosen banyak diuber urusan administrasi terkait keharusan menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Lama-lama, kita tidak lagi punya kesempatan.
Mohammad Nanda Widyarta: Saya mungkin bukan ahli sejarah pergerakan. Akan tetapi, yang saya tahu, pergerakan biasanya merespon suatu kondisi. Sebagai contoh, LSAI dan AMI terbentuk di masa orde baru, meskipun tidak secara langsung bersifat politik, tetapi merespon ketidakpuasan atas sesuatu yang terjadi di masa itu. Saat ini, permasalahan apa yang perlu direspon jika kita ingin membuat pergerakan? Apakah AI? Akan tetapi, bukankah kita malah menikmati AI? Apa sebenarnya ada permasalahan yang tidak kita sadari? Apa yang perlu kita lakukan untuk dapat menyadari suatu kondisi?
Sutrisno Murtiyoso: Saya melihat adanya gejala yang menandakan sikap dan gaya hidup global yang sudah mulai seragam. Budaya Indonesia menjadi seakan-akan tidak lagi penting. Kita berusaha setingkat dengan masyarakat global yang dianggap lebih baik, yang memang menjadi mentalitas masyarakat negara pasca penjajahan. Itu yang menurut saya perlu ditanggulangi. Dengan aliran informasi yang semakin mudah, hal-hal terkait negara luar pun semakin mudah dikonsumsi. Saya hanya khawatir identitas kita semakin dilupakan.
Paristiawang Nugraha: Dalam membicarakan pergerakan, saya merasa, setiap generasi memiliki tantangannya masing-masing. Tantangan generasi baby boomer mungkin adalah sulitnya informasi sehingga mereka menjadi giat mencari. Sementara itu, saat ini, informasi bisa didapatkan dengan sangat cepat. Itu yang mungkin membuat kita berpikir, “Untuk apa lagi perjuangan arsitektur Indonesia dilakukan?” Lalu, fundamental apa yang sebenarnya perlu dipegang kaum muda untuk melanjutkan tongkat estafet arsitektur Indonesia?
Sutrisno Murtiyoso: Jawaban sederhananya adalah berpikir kritis. Sulitnya, pendidikan di Indonesia membuat kita terbiasa dengan hafalan. Ketika menghadapi teknologi tinggi, kita cenderung hanya mengambil data yang diinginkan, tanpa menggali lebih jauh. Kita menjadi mudah terbawa media sosial. Padahal, ilmu di media sosial banyak yang hanya bersifat permukaan. Pendidikan dasar kita perlu diperbarui. Nomor satunya melalui pendidikan guru. Pada akhirnya, dalam kacamata nasional, kebutuhan kita sebenarnya ada di luar arsitektur.
Yuswadi Saliya: Saya ingin bernostalgia mengenai LSAI di masa lalu. Dulu, kita punya program LNPSA (Lokakarya Nasional Pengajaran Sejarah Arsitektur) yang semula diarahkan untuk dosen-dosen sejarah, tetapi kemudian dikembangkan ke pemahaman sejarah lebih luas, sehingga lebih banyak dosen dari disiplin lain pun bisa turut bergabung. Apa yang dibicarakan di diskusi ini bisa menjadi benih-benih pembicaraan lebih lanjut. Isu-isu sebenarnya merupakan ladang yang tidak ada habisnya. Saya berharap LNPSA bisa kembali digalakkan. Saya rasa perputaran dapat lebih cepat terjadi jika kita tidak hanya menyasar peminat individual, tetapi juga kelembagaan. Akan tetapi, sumbangan OMAH Library di sini sudah cukup besar untuk membangkitkan kembali minat disiplin kesejarahan yang sudah banyak dianggap tidak relevan.
Realrich Sjarief: Dalam pandangan saya, Pak Sutrisno Murtiyoso sedang menggawangi nilai di atas kekhawatiran akan banyaknya korban. Dari sini, saya melihat pentingnya kekritisan yang terkait dengan sebuah kerapuhan. Kami di OMAH Library siap membantu dengan kompleksitas begitu besar yang mungkin sulit diurai. Menurut saya, posisi OMAH Library sebenarnya tidak terlalu diperlukan mengingat sudah banyaknya lubang pengetahuan tertutup oleh akademisi dan LSAI. Kami hanya riang gembira membantu apa yang bisa kami bantu. Wish all the best. Semoga yang terbaik yang akan muncul. Saya melihat bahwa diskusi LSAI selalu sangat bagus untuk dijadikan pemantik riset-riset dan perenungan-perenungan selanjutnya. Terima kasih Pak Sutrisno Murtiyoso yang sudah mau turun gunung berembuk dengan kami yang muda-muda.
@omahlibrary @rumaharsitekturindonesia @guhatheguild
#rumaharsitekturindonesia #omahlibrary #guhatheguild #ArchitecturalDiscussions #librarydialoguehub #architecturestudentlife #arsitekturmumpuni #jakarta #indonesia
Tentang OMAH Events lainnya di bawah ini: